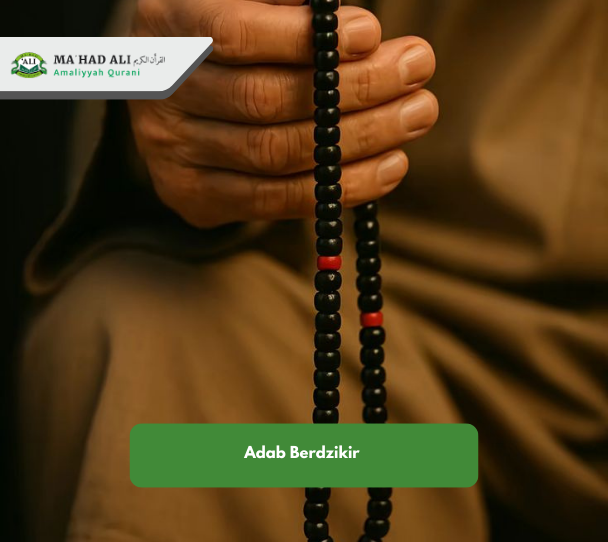Penyusun : Sarnina Ningsih
Pendahuluan
Dzikir dan istighfar merupakan dua amalan spiritual yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Dzikir, yang secara etimologis berarti “mengingat”, adalah bentuk pengingatan seorang hamba kepada Allah SWT melalui penyebutan nama-nama-Nya, pujian, dan kalimat-kalimat tayyibah. Sementara istighfar adalah permohonan ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Kedua amalan ini bukan sekadar rutinitas verbal, melainkan ibadah yang mengandung dimensi spiritual mendalam yang menghubungkan hamba dengan Khaliq-nya (Al-Qaradhawi, 2000).
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ
“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 152)
Ayat ini menunjukkan bahwa dzikir kepada Allah akan dibalas dengan dzikir Allah kepada hamba-Nya, sebuah balasan yang tak ternilai harganya. Namun, untuk meraih keutamaan dzikir secara maksimal, seorang muslim perlu memahami dan mengamalkan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (An-Nawawi, 2006). Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang adab dalam berdzikir dan beristighfar, meliputi waktu-waktu utama, tata cara menyebut nama Allah, harmonisasi dzikir lisan dan hati, serta pentingnya konsistensi dalam wirid harian.
Waktu-waktu Utama Berdzikir
Islam mengajarkan bahwa dzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 191. Namun, terdapat waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan khusus untuk berdzikir, di mana pahala dan keberkahan berlipat ganda (Asy-Syaukani, 1994).
Pertama, waktu sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda:
يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ
“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman: ‘Siapa yang berdoa kepada-Ku maka akan Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku beri, siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni.'” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab yang sangat istimewa untuk berdzikir, berdoa, dan beristighfar. Pada waktu ini, Allah SWT “turun” dengan cara yang sesuai dengan keagungan-Nya, memberikan kesempatan emas bagi hamba-Nya untuk mendekatkan diri (Ibn Hajar al-Asqalani, 1996).
Kedua, waktu setelah shalat fardhu. Imam An-Nawawi (2006) menyatakan bahwa dzikir setelah shalat lima waktu memiliki keutamaan khusus karena dilakukan setelah menunaikan kewajiban utama. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai dzikir setelah shalat, seperti membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali, serta membaca ayat Kursi dan beberapa dzikir ma’tsur lainnya.
Ketiga, waktu pagi dan petang. Dzikir pagi (ba’da Subuh hingga terbit matahari) dan dzikir petang (ba’da Ashar hingga terbenam matahari) merupakan waktu-waktu yang sangat dianjurkan. Dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai dzikir untuk dibaca pada waktu-waktu ini, termasuk membaca Sayyidul Istighfar, dzikir perlindungan, dan surat-surat pilihan dari Al-Qur’an (Al-Albani, 2002).
Keempat, antara adzan dan iqamah. Rasulullah SAW bersabda: “Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Waktu singkat namun penuh berkah ini adalah momentum ideal untuk memperbanyak dzikir dan doa (Al-Mubarakfuri, 1999).

Adab Menyebut Nama Allah
Menyebut nama Allah SWT (Asma’ul Husna) merupakan inti dari dzikir. Namun, terdapat adab-adab penting yang harus diperhatikan agar dzikir bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah (Shihab, 2018).
Pertama, menyebut dengan penuh ta’zhim (pengagungan). Nama Allah bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan nama yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Oleh karena itu, ketika menyebut nama Allah, seorang muslim harus merasakan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan-Nya dalam hati. Al-Ghazali (1993) menekankan bahwa dzikir yang hakiki adalah dzikir yang disertai dengan kehadiran hati (hudhur al-qalb) dan perenungan akan makna nama-nama Allah yang disebut.
Kedua, menggunakan nama-nama yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Allah berfirman:
وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖوَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَاۤىِٕهٖ ۗسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
“Dan Allah memiliki Asma’ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf [7]: 180)
Ayat ini menegaskan pentingnya menggunakan nama-nama Allah yang shahih dan tidak menyimpang dari yang telah diajarkan. Ibn Qayyim al-Jauziyyah (2003) menjelaskan bahwa menyebut nama Allah dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menambah atau mengurangi nama-nama-Nya, termasuk dalam kategori ilhad (penyimpangan) yang dilarang.
Ketiga, bersuci dan dalam keadaan yang layak. Meskipun dzikir diperbolehkan dalam berbagai kondisi, para ulama menganjurkan agar berdzikir dalam keadaan suci dari hadats dan najis, terutama untuk dzikir-dzikir yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kalam Allah dan nama-nama-Nya yang mulia (Az-Zuhaili, 2010).
Keempat, dengan suara yang sedang (tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 205: “Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang.” Ibnu Katsir (2000) menafsirkan ayat ini bahwa dzikir sebaiknya dilakukan dengan suara yang khusyu’, tidak berlebihan dalam mengeraskan suara sehingga mengganggu orang lain atau terkesan riya’.
Dzikir dengan Lisan dan Hati
Dzikir yang sempurna adalah dzikir yang melibatkan lisan dan hati secara bersamaan. Imam Al-Ghazali (1993) dalam kitab Ihya’ Ulumuddin membagi dzikir menjadi tiga tingkatan: dzikir lisan tanpa hati (tingkat pemula), dzikir lisan dan hati (tingkat menengah), dan dzikir hati yang mendominasi lisan (tingkat tinggi).
Dzikir lisan merupakan pengucapan kata-kata dzikir dengan mulut. Ini adalah bentuk dzikir yang paling dasar dan mudah dilakukan. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai lafal dzikir yang mudah diucapkan namun memiliki pahala yang besar. Dalam hadits shahih, Rasulullah SAW bersabda:
كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
“Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Yang Maha Pengasih: Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil ‘Azhim.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa dzikir lisan yang sederhana pun memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Namun demikian, dzikir lisan yang tidak disertai dengan kehadiran hati belumlah sempurna (Ibn Rajab al-Hanbali, 1998).
Dzikir hati adalah mengingat Allah dengan sepenuh hati, merasakan kehadiran-Nya, dan merenungkan kebesaran-Nya. Ini merupakan hakikat dzikir yang sesungguhnya. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (1997) menyatakan bahwa dzikir hati lebih utama daripada dzikir lisan semata, karena dzikir hati menunjukkan kesungguhan dan keikhlasan dalam beribadah.
Harmonisasi keduanya merupakan bentuk dzikir yang paling sempurna. Al-Qurthubi (2006) menjelaskan bahwa dzikir yang ideal adalah ketika lisan menyebut nama Allah sementara hati hadir, merenungi, dan merasakan makna dari dzikir yang diucapkan. Inilah dzikir yang akan membawa ketenangan jiwa, sebagaimana firman Allah:
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُۘ
“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 28)
Para praktisi dzikir yang berpengalaman menyarankan untuk memulai dengan dzikir lisan sambil berusaha menghadirkan hati, kemudian secara bertahap meningkatkan kualitas kehadiran hati hingga akhirnya hati yang memimpin, dan lisan mengikuti (As-Samarqandi, 2005).

Konsistensi dalam Wirid Harian
Konsistensi (istiqamah) dalam menjalankan wirid harian merupakan kunci untuk meraih manfaat dzikir secara maksimal. Rasulullah SAW bersabda:
أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ
“Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pertama, memilih wirid yang sesuai kemampuan. Para ulama menganjurkan agar setiap muslim memiliki wirid harian yang realistis dan dapat diamalkan secara konsisten. Lebih baik sedikit tetapi rutin daripada banyak tetapi tidak konsisten. Wirid minimal yang dianjurkan meliputi: dzikir pagi-petang, dzikir setelah shalat fardhu, membaca Al-Qur’an minimal satu halaman, dan istighfar minimal 100 kali sehari (Al-Munajjid, 2015).
Kedua, mencatat dan mengevaluasi. Dalam praktik spiritual Islam kontemporer, banyak praktisi yang menggunakan buku wirid atau aplikasi digital untuk mencatat dan memantau konsistensi wirid harian mereka. Metode ini terbukti efektif dalam menjaga komitmen dan membangun kebiasaan positif (Shihab, 2018).
Ketiga, memiliki waktu khusus yang tetap. Al-Ghazali (1993) menyarankan agar wirid dilakukan pada waktu yang tetap setiap hari. Hal ini akan membantu membentuk kebiasaan dan memudahkan konsistensi. Misalnya, dzikir pagi selalu setelah shalat Subuh, dzikir petang setelah shalat Ashar, dan istighfar sebelum tidur.
Keempat, tidak mudah putus asa ketika terlewat. Ibn Hajar al-Asqalani (1996) menjelaskan bahwa jika seseorang terlewat melakukan wirid hariannya karena uzur, hendaknya ia tidak berputus asa dan segera mengganti atau melanjutkan kembali. Yang terpenting adalah niat untuk istiqamah dan terus berusaha.
Kelima, bertahap dalam peningkatan. Untuk pemula, mulailah dengan wirid yang sederhana dan sedikit, kemudian tingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan kemampuan spiritual. Pendekatan bertahap ini lebih sustainable dan mencegah kejenuhan (Al-Munajjid, 2015).
Konsistensi dalam wirid harian akan membentuk karakter spiritual yang kuat, menjaga hati dari kelalaian, dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Para salafush shalih dikenal sangat menjaga wirid mereka, bahkan dalam kondisi sakit atau safar, mereka tetap berupaya menunaikannya (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2003).
Kesimpulan
Adab dalam berdzikir dan beristighfar merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas dan penerimaan ibadah dzikir di sisi Allah SWT. Pemahaman yang komprehensif tentang waktu-waktu utama berdzikir—seperti sepertiga malam terakhir, setelah shalat, waktu pagi dan petang—membantu seorang muslim mengoptimalkan ibadahnya dan meraih keberkahan maksimal.
Adab menyebut nama Allah dengan penuh ta’zhim, menggunakan nama-nama yang shahih, dalam keadaan suci, dan dengan suara yang sedang mencerminkan penghormatan dan kesungguhan seorang hamba. Sementara itu, harmonisasi antara dzikir lisan dan dzikir hati menghadirkan kualitas spiritual yang lebih mendalam, membawa ketenangan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah.
Konsistensi dalam menjalankan wirid harian, meskipun dalam jumlah yang sederhana, merupakan kunci untuk meraih manfaat jangka panjang dari dzikir. Amalan yang sedikit namun istiqamah lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak namun terputus-putus. Dengan memahami dan mengamalkan adab-adab ini, seorang muslim tidak hanya menjalankan ritual, tetapi menjalani kehidupan spiritual yang bermakna dan transformatif.
Wallahu a’lam bish-shawab. Semoga artikel ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Aamiin.
Daftar Pustaka
Al-Albani, M. N. (2002). Shahih sunan Abi Dawud. Maktabah al-Ma’arif.
Al-Ghazali, A. H. (1993). Ihya’ ulumuddin (Terj. Ismail Yakub). Faizan.
Al-Mubarakfuri, M. A. R. (1999). Tuhfatul ahwadzi bi syarh Jami’ at-Tirmidzi. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Munajjid, M. S. (2015). Kitab al-wirid al-yawmi. Islamic Propagation Office.
Al-Qaradhawi, Y. (2000). Al-ibadah fi al-Islam. Maktabah Wahbah.
Al-Qurthubi, M. A. (2006). Al-jami’ li ahkam al-Qur’an. Muassasah ar-Risalah.
As-Samarqandi, N. M. (2005). Tanbih al-ghafilin. Dar Ibn Hazm.
Asy-Syaukani, M. A. (1994). Fath al-qadir al-jami’ bayna fannay ar-riwayah wa ad-dirayah min ‘ilm at-tafsir. Dar al-Wafa.
Az-Zuhaili, W. (2010). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
Ibn Hajar al-Asqalani, A. A. (1996). Fath al-bari bi syarh Shahih al-Bukhari. Dar as-Salam.
Ibn Katsir, I. U. (2000). Tafsir al-Qur’an al-‘azhim. Dar Thayyibah.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, M. A. B. (2003). Al-wabil ash-shayyib min al-kalim ath-thayyib. Dar Ibn Khuzaimah.
Ibn Rajab al-Hanbali, Z. A. R. (1998). Jami’ al-‘ulum wa al-hikam. Muassasah ar-Risalah.
Jailani, A. Q. (1997). Al-fath ar-rabbani. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
An-Nawawi, Y. S. (2006). Al-adzkar an-nawawiyyah. Dar Ibn Hazm.
Shihab, M. Q. (2018). Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an (Vol. 1-15). Lentera Hati.